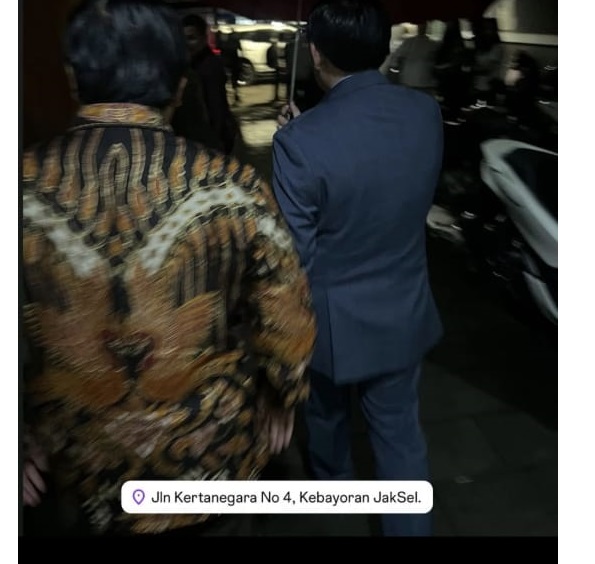Wartawan Tempo Tak Boleh Salah
Si pengirim, yang memposisikan diri mewakili suara orang kebanyakan, bertanya: “Kok, Tempo bisa begini”?
Saya jawab, “Inilah yang membedakan media bermartabat dengan media pendengung yang diternak politikus dan pendukungnya”. Media otoritatif seperti Tempo, bila melakukan kesalahan kecil sekalipun, dengan segera minta maaf secara terbuka.
Pengakuan atas kekeliruan itu adalah nilai-nilai yang mengharuskan mereka mendapatkan evaluasi secara etik dari dalam. Berbeda dengan media pendengung yang derajat salah dan benarnya ditentukan oleh siapa majikannya.
Hidup menjadi tidak gampang ketika Anda menjadi wartawan Tempo. Anda tidak boleh benar, juga tak boleh salah.
Kalau Anda menulis benar, Anda akan dituduh nyinyir, punya kepentingan, atau menjadi corong suatu kelompok.
Kalau salah, Anda akan dirundung habis-habisan. Kesalahan Anda ditunggu dan dicari-cari. Sekali terpeleset, orang akan bersorak dan segera menggempurnya. Dari segala penjuru.
Semula, gejala ini diharapkan mendorong lahirnya “demokratisasi berita” dan meluasnya partisipasi dalam jurnalisme warga, juga lambang dari kebebasan.
Namun sisi gelap dan kontradiksi “demokratisasi media” ini dengan segera muncul didorong oleh faktor klasik, yakni modal dan kekuasaan.
Menurut Karl Marx, “Mereka yang menguasai kekuatan produksi suatu masyarakat akan menguasai gagasan masyarakat itu”.
Mereka yang menguasai uang dan kekuasaan politik otomatis menguasai akses dan produksi media sehingga mereka menguasai juga perbincangan dalam masyarakat.
Di Indonesia, simpul sisi gelap ekonomi-politik media baru ini dimulai pada 2014. Untuk pertama kali dalam sejarah media sosial, para pemengaruh dan pendengung politik terlibat dalam pemilihan umum.
Sejak saat itu muncul sejenis kerja serta sistem seleksi politik baru dalam masyarakat kita.
Aktivitas di media sosial menjadi profesi dan instrumen untuk menunjukkan keberpihakan dan loyalitas, lengkap dengan pasukan, komando, dan markas. Fenomena ini menandai lahirnya relasi baru penguasa-media.
Para elite pun melihat penguasaan media sosial ini lebih efisien dalam memobilisasi politik, menjaring dukungan, dan mengawasi pengkritik.
Menguasai konsultan politik yang kuat dan membina beberapa kelompok pendengung andal lebih efektif ketimbang mencoba mempengaruhi media yang terlembaga.
Sebelum era media sosial, para elite dan calon presiden biasa sowan ke kantor-kantor media besar. Sejak 2014, elite dan calon presiden hanya sesekali berkunjung ke redaksi-redaksi media besar.
Mereka lebih senang membelanjakan waktu bertemu dengan para pemengaruh media sosial.
Influencer atau pemengaruh, pendengung, dan berita bohong adalah penyebab pertama terbelahnya masyarakat.
Masyarakat yang terbelah adalah lahan subur bagi para pemimpin dan elite-elite yang inkompeten untuk terus berkuasa dan memimpin.
Dalam masyarakat yang terbelah, ukuran-ukuran yang dipakai orang untuk memilih pemimpin biasanya juga melorot, minimalis, apa adanya.
Ini yang melahirkan pragmatisme dalam prinsip lesser evil ketika memilih pemimpin.
Dalam konteks ini, di muka setiap wartawan Tempo, menganga lebar dua situasi yang membikin hidup mereka makin sulit: pertama, dalam masyarakat yang terbelah, tugas pertama jurnalistik adalah mencari kebenaran obyektif. Ini nyaris menjadi perjuangan yang tak mungkin.
Mengapa?
Karena media akan terus didorong untuk mengambil sikap partisan. Masyarakat yang terbelah membaca berita sesuai dengan skema primordialnya masing-masing.
Mereka hanya percaya kepada berita yang mereka suka. Masyarakat Indonesia kini adalah ruang gema (eco chamber) raksasa yang merespons setiap berita dengan bias konfirmasi.
Situasi kedua yang membuat hidup wartawan Tempo penuh cobaan adalah tekanan dari penguasa dan elite yang membiakkan pembelahan serta menyebarkan ketakutan dalam upaya menjustifikasi dan mereproduksi kekuasaan mereka.
Bill Kovach mengatakan salah satu ciri jurnalisme adalah kritik. Kritik mengasumsikan optimalisasi dari kerja akal budi dalam upaya membuka selubung kekuasaan dan kepentingan.
Fungsi inilah yang meletakkan jurnalisme menjadi bagian civil society. Elite yang memelihara pendengung adalah elite yang tidak mau mendengar kritik.
Ia memerlukan pendengung untuk menyenangkan diri sendiri dan menegasikan kritik. Dalam sebuah rezim populis, pendengung adalah resonansi dari ego si pemimpin.
Media sosial, pendengung, dan pemimpin populis kompatibel satu dengan yang lain.
Menurut Nadia Urbinati, ahli politik dari Columbia University, inti populisme adalah mendegradasikan fungsi lembaga-lembaga politik formal dengan mengandalkan bentuk-bentuk politik informal.
Pendengung dan “kuasi-relawan” pun menjadi efektif memenuhi panggilan hasrat populis itu, karena sifatnya yang informal dan lepas dari tanggung jawab publik.
Mereka bisa bekerja lebih tangkas dalam memproduksi dan merepetisi narasi-narasi kotor karena mereka tak harus merujuk prosedur dan etika serta rambu-rambu Dewan Pers.
Media publik di Indonesia mulai mengalami rongrongan jauh sebelum digitalisasi menjadi keharusan dan “media baru” menjadi tantangan.
Rongrongan utama datang dari fenomena oligarki. Pemilik media adalah politikus yang menggunakan kekuasaan sebagai sarana mengakumulasi sumber daya ekonomi.
Dalam oligarki, pemisahan antara penguasa politik dan penguasa ekonomi menjadi kabur, demarkasi yang publik dan yang privat menjadi lebur.
Relasi oligarki tersebut bukan hanya menekan kerja para jurnalis dan media publik di bawahnya, juga dengan mudah menyeret media dan jurnalis menjadi partisan sesuai dengan arah angin dan preferensi politik pemiliknya, sebagaimana terjadi dalam dua pemilu terakhir.
Di sini independensi media dan fungsi kritik jurnalisme menjadi semaput.
Tempo adalah media yang selalu bersemangat menampilkan tokoh yang mereka pandang punya pikiran terbuka dan demokratis.
Namun Tempo juga adalah media pertama yang melancarkan kritik dan gugatan terhadap tokoh itu saat mereka berkuasa.
Sejak era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hingga Boediono dan kini Jokowi, Tempo memiliki modus operandi hubungan dengan para penguasa di Indonesia seperti itu. Kedekatan personal mereka tidak menghalanginya melancarkan kritik.
Hubungan Tempo dengan para tokoh politik itu bisa kita sebut sebagai relasi “crimacy”: critical intimacy, yakni keintiman yang kritis sekaligus berjarak.
Dengan relasi seperti itu, wartawan Tempo tidak boleh benar. Sebab, mereka akan segera berhadap-hadapan dengan para mantan jurnalis dan senior yang terus intim tanpa kritik dengan penguasa.
Di masa Soeharto, basis eksistensi dan kendali sebuah media oleh rezim penguasa berada di selembar SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers).
Media mesti menjadi corong pembangunan atau setidaknya mesti pintar mengatur kata. Jika salah, pemerintah akan mencabut SIUPP mereka yang berakibat media mereka ilegal.
Pembredelan Tempo, Detik, dan Editor pada 1994 serta pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, adalah bukti kontrol kekuasaan terhadap informasi di masa lalu.
Setelah SIUPP tak ada lagi, penguasa mencekik wartawan dengan melarang badan usaha milik negara dan perusahaan swasta beriklan di media-media “yang tidak bersahabat dengan pemerintah”.
Wartawan Tempo tak boleh salah karena menulis berita kini jadi aktivitas banal yang nilainya dihitung dari konversi klik.
Industri media diinvasi oleh “liquid live”, cepat menulis, cepat mengunggah, dan dibuat seheboh-hebohnya.
Digitalisasi membuat media besar menderita kepribadian ganda: ingin memelihara mutu dan integritas sekaligus berlomba mengejar klik yang melahirkan berita-berita sampah tapi dibaca banyak orang.
Maka, untuk melawan kebanalan itu, wartawan Tempo mesti salah, di jalan yang benar.
BACA JUGA: majalah EKSEKUTIF edisi mei 2022